Oleh: Ifanko Putra
Pembangunan terus tumbuh dan berkembang luas seiring perputaran zaman. Pembangunan mengiringi setiap peradaban demi peradaban manusia sejak manusia pertama menempati bumi dan hanya akan berakhir setelah era manusia terakhir punah.
Pembangunan adalah prakondisi dari kehidupan manusia itu sendiri.
Dalam peradaban modern, khususnya di Indonesia, terdapat suatu konsep pembangunan, yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Konsep pembangunan berkelanjutan ini sendiri, mengutip pendapat dari Prof. Emil Salim, adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.
Sebagaimana telah diketahui bersama, alam memiliki banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan dalam pembangunan dan menunjang kehidupan manusia.
Salah sumber daya alam tersebut adalah mangrove atau hutan bakau. Karena geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, mangrove tersebar luar di sebagian besar daerah mulai dari Sabang hingga Merauke. Namun demikian, meski populasi mangrove cukup melimpah, eksploitasi dan pemanfaatannya harus seimbang dengan pelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan atau alam itu sendiri.
Beberapa bulan yang lalu, penulis berkunjung ke salah satu daerah di pesisir Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Daerah ini memiliki kontur tanah gambut atau berawa, Kondisi ini menyebabkan setiap bangunan yang akan dibangun di daerah ini, terutama bangunan permanen harus terlebih dahulu diberi cerucuk di bawah pondasi.
Bahan baku utama pembuatan cerucuk adalah kayu bakau karena sifat ketahanannya terhadap air, oleh karenanya kebutuhan akan kayu bakau menjadi sangat tinggi. Kebutuhan tinggi, menjadikan kayu bakau menjadi satu rantai komoditas ekonomi. Perambahan besar terhadap kayu bakau menjadi tidak terhindarkan karena permintaan yang tinggi.
Di alam sendiri, hutan bakau atau mangrove berfungsi untuk menjaga kelestarian ekosistem makhluk hidup di sekitarnya, mencegah terjadinya bencana dari meluapnya air laut kedarat dan juga berfungsi sebagai penyumbang oksigen yang cukup besar.
Perambahan besar terhadap kayu bakau yang tidak diimbangi dengan reboisasi dan pelestarian kembali telah membawa dampak buruk bagi masyarakat di Indragiri Hilir dalam beberapa waktu ini. Masyarakat yang umumnya petani komoditas tanaman kelapa merasakan dampak kerusakan kebun mereka akibat terendam banjir rob.
Indragiri Hilir memiliki kawasan hutan mangrove yang cukup luas, kurang lebih 133.972 ha dari total kawasan hutan yang mencapai 1.024.025 ha. Namun, kerusakan hutan mangrovenya sudah lebih 50 persen atau sekitar 67.000 hektar.
Kawasan hutan mangrove tersebut tersebar ditujuh kecamatan yakni, Kuala Indragiri, Mandah, Tanah Merah, GAS, Reteh, Kateman dan Enok atau disepanjang 553,74 kilometer pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.
Daerah ini selalu terendam banjir dalam periode tertentu karena berada di kawasan pesisir. Namun, akibat eksploitasi hutan mangrove yang terus masiv dilakukan tanpa diseimbangkan dengan pelestariannya, volume banjir itu kian waktu terus meninggi, sehingga banyak merusak perkebunan masyarakat. Pemerintah mengakali dengan memasang tanggul di sejumlah titik pingggiran sungai menggunakan alat berat, namun itu belum dapat banyak membantu karena luasnya daerah tersebut. Pemerintah setempat tentu saja harus mengatasi puncak masalah ini demi kelangsungan jangka panjang, dengan melestarikan mangrove secara besar besaran.
Berbeda dengan Indragiri Hilir, penulis juga mengamati kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang terdampak oleh geliatnya pembangunan. Perambahan dan peluasan pemukiman di daerah ini menyebabkan populasi mangrove semakin berkurang waktu demi waktu.
Di Batam, kayu bakau dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat arang dan menjadi komoditas ekspor terutama ke Singapura. Hal ini telah terjadi cukup lama. Selain itu, pembangunan yang pesat hingga ke kawasan pesisir, manjadikan mangrove harus dirambah atau ditimbun dan beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman.
Dampaknya, masyarakat melayu lokal mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang menetap di daerah ini sejak nenek moyang mereka mengeluhkan semakin sulitnya mencari ikan hari demi hari.
Para nelayan harus terpaksa mencari ikan lebih jauh lagi ke tengah laut dengan konsekuensi harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk bahan bakar kendaraan laut mereka.
Dampak lain, namun memerlukan kajian khusus adalah berkurangnya kadar udara sehat yang dihasilkan oleh hutan mangrove.
Pelestarian mangrove dipandang perlu, karena Kota Batam merupakan daerah kecil namun dijadikan kota industri, yang menghasilkan banyak sekali polusi baik dari pabrik-pabrik industri maupun dari asap kendaraan.
Perihal pembangunan berkelanjutan, implementasinya diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Demikian juga halnya dengan pemanfaatan dan kelestarian mangrove sendiri, telah diatur dalam berbagai regulasi yang ada.
Peraturan tentang pemanfaatan dan pelestarian mangrove ini dibuat oleh pemerintah, menjelaskan fakta betapa pentingnya kelestarian mangrove untuk kelangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Peraturan ini misalnya, UU 27 tahun 2007 jo UU 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Presiden No, 121 tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil, dan Permenko Perekonomian No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.
Namun, dalam rangka menciptakan pengawasan, dan penindakan yang lebih jelas dan tepat sasaran, penulis berpandangan bahwa setiap daerah pesisir yang bergantung dan melakukan pemanfaatan terhadap hutan mangrove perlu mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan melalui sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang khusus membahas tentang mangrove dan kelestarian ekosistem lingkungan pinggir pantai.
Meski telah diatur dengan peraturan dan regulasi yang lebih tinggi, Peraturan Daerah ini, dikhususkan dalam rangka menjaga ekosistem mangrove di daerah tertentu dari kerusakan yang lebih parah.
Sebab hanya daerah masing-masing yang lebih tahu tentang derahnya sendiri dan agar memudahkan melakukan penindakan, sehingga tidak bergantung lagi kepada penindakan yang dilakukan oleh Gakkum KLHK pusat, sebagaimana yang terjadi selama ini. Namun cukup melibatkan daerah yang melakukan menindakan berkordinasi dengan KLHK pusat. Hal ini akan lebih efektif untuk mengawasi, mencegah dan menindak pelaku eksploitasi mangrove yang tidak sesuai aturan.**

































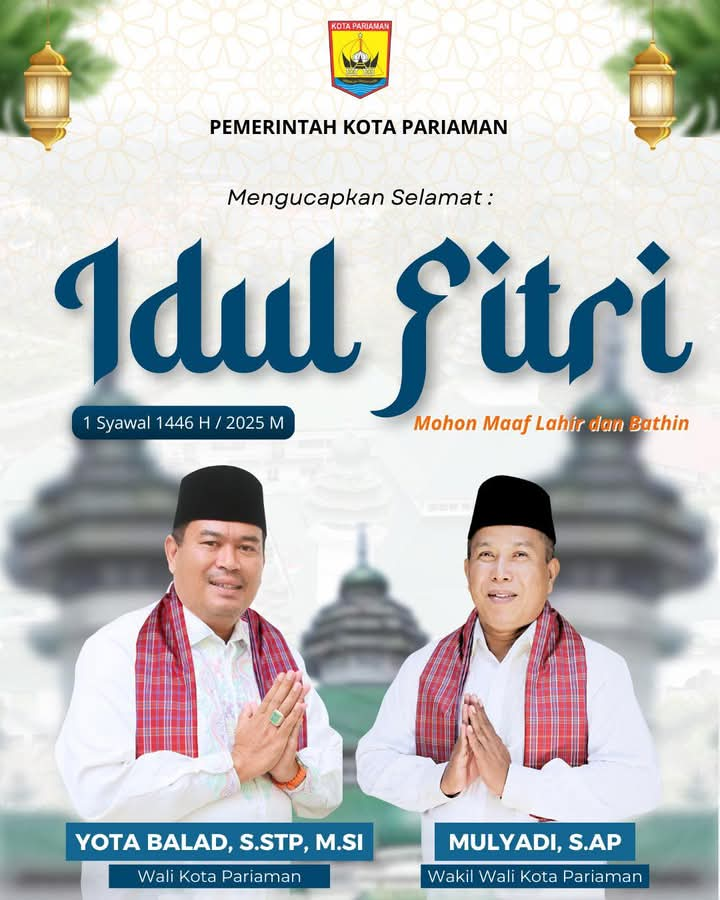





Discussion about this post